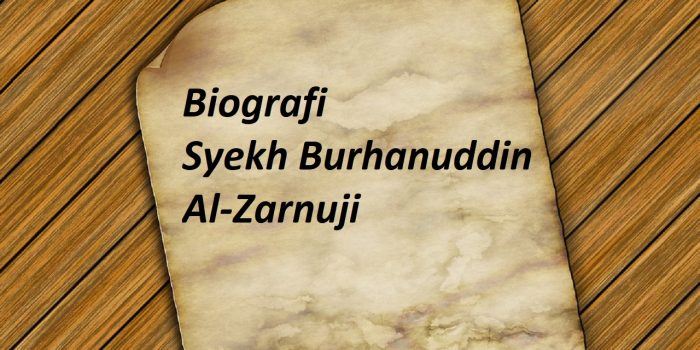Kebijakan Islam di Masa kepemimpinan Umar Bin Khattab
Siapa yang tidak mengenal Umar bin Khattab? Beliau adalah salah satu dari 4 orang khulafaur rasyidin. Sebagai salah seorang sahabat nabi terbaik, tentu saja banyak orang yang mengagumi Umar bin Khattab. Selain ketegasan dan ketangkasannya, kepemimpinan di masa Umar merupakan kepemimpinan terbaik.
Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah meninggalnya Abu Bakar as Shiddiq. Masa kepemimpinan Umat bin Khattab adalah selama 10 tahun 73 hari (13-23 Hijriah). Sebagai khalifah, Umar dikenal sebagai sosok yang berani, tanggung jawab, adil, sederhana, dan cerdas. Ketika memimpin jazirah Arab, banyak sekali kebijakan yang dicetuskan beliau.
Mengutip buku berjudul Umar bin Khattab Ra. karangan Abdul Syukur al-Azizi (2021: 213), dalam sepuluh tahun kepemimpinan Umar bin Khattab, banyak sekali kebijakan yang beliau keluarkan, diantaranya: mendirikan departemen pedidikan, membuat peraturan gaji terhadap pegawai-pegawai pemerintah, membangun Baitul Mal, mencetak mata uang, memberntuk kesatuan tentara untuk melindungi daerah tapal batas, mengangkat para hakim, menyelenggarakan hisbah dan sebagainya.
Umar bin Khhatab juga meletakan prinsip-prinsip demokratis dalam pemerintahannya. Pemerintah Umar menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara dan tidak ada hak istimewa. Selain itu, Umar berjasa besar dalam mengembangkan perekonomian masyarakat selama masa pemerintahannya. Beliau dianggap sebagai khalifah yang mampu mensejahterakan rakyatnya.
Keberhasilan Umar bin Khattab mengembangkan Islam hingga ke luar jazirah Arab berdampak pada dinamika sosial umat muslim. Sebelum penaklukan, penduduk negara islam terdiri dari etnis Arab dan minoritas Yahudi. Setelah penaklukan, jumlah orang yang beragama Islam naik pesat, sehingga kelompok-kelompok sosial dalam komunitas Islam semakin beragam dan kompleks.
Bersamaan dengan hal tersebut, terjadi pula asimilasi antar berbagai kelompok, terutama dibangunnya Kota Kufah sebagai tempat bertemunya berbagai kelompok dan suku. Mobilitas penduduk semakin intens. Ibu kota Madinah tidak hanya dikunjungi suku Arab, melainkan orang-orang nin arab. Begitu juga sebaliknya, orang-orang Arab dapat mengunjungi dan menetap di Mesir, Syria, Persia dan wilayah-wilayah kekuasan. Hal tersebut menimbulkan kontak dan saling mengambil unsur-unsur kebudayaan.
Dalam beberapa ketentuan hukum, Umar bin Khattab terus berijtihad dengan sungguh-sungguh yang belum pernah dilakukan pada masa Rasulullah shallallahu ‘alihi wa sallam dan Abu Bakar as Shiddiq. Umar juga membuat peraturan ekonomi dan sosial yang begitu terperinci yang menuntut perhitungan bersih dan kemurnian prinsip-prinsip agama yang benar. Ada banyak kebijakan yang diterapkan Umar semasa kepemimpinannya. Berikut ini adalah beberapa di antaranya:
1. Kebijakan dalam bidang pendidikan dan pengajaran
Selama kepemimpinannya, Umar menerapkan banyak kebijakan. Termasuk juga yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Di bawah kepemimpinannya, Al-Qur’an diajarkan dan disebarkan ke seluruh pelosok negeri.
Bersama dengan itu, dibangun juga berbagai tempat belajar dan madrasah yang mempelajari Al-Qur’an, hadits, fiqh, dan berbagai ilmu agama. Para siswa dari madrasah tersebut diwajibkan untuk menghafal minimal 5 surat dari Al-Qur’an. Yaitu surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-hajj, An-Nur, dan Al-Maidah.
Ada beberapa madrasah yang dibangun di Makkah, Madinah, Bashrah, Kufah, Syam, dan Mesir. Setiap madrasah tersebut memiliki guru besarnya masing – masing yang berasal dari kalangan sahabat.
Beberapa sahabat yang ahli hadits dan fiqh pun diminta untuk mengajar. Di antaranya adalah Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Muadz bin Jabal, Abu Darda, Ubadah bin Shamit, Imran bin Hashim, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas’ud, Ali bin Abu Thalib, dan termasuk juga Aisyah binti Abu Bakar.
2. Kebijakan pembangunan masjid
Pembangunan masjid juga menjadi perhatian Umar bin Khattab. Beliau memerintahkan para gubernur di Bashrah, Kufah, Mesir, dan para wali di sepanjang wilayah Syam untuk membangun masjid besar di pusat kota, dan juga satu masjid di setiap kampung dan suku.
Sementara Masjidil Haram dan masjid Nabawi pun juga dibangun agar menjadi lebih luas. Serta ditambahkan beberapa fasilitas seperti lampu gantung, wewangian, dan juga alas tikar.
3. Kebijakan kesehatan masyarakat
Selain memperhatikan agama masyarakatnya, Umar juga memperhatikan kesehatan masyarakat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, beliau banyak mendirikan klinik dan rumah sakit, serta pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
4. Kebijakan pembagian wilayah administratif
Pada masa Umar juga pembagian wilayah administratif mulai diberlakukan. Umar membagi wilayah Islam menjadi beberapa provinsi dan distrik. Yaitu Semenanjung Arabia, Semenanjuk Irak, Persia, Mediterania Timur, dan juga Afrika Utara.
Setiap provinsi tersebut memiliki struktur administratif masing – masing yang terdiri dari gubernur, sekretaris wilayah, perwira militer, dinas perpajakan yang juga menjadi petugas zakat, pejabat keuangan negara, dan dinas kehakiman.
5. Kebijakan pemisahan antara eksekutif dan yudikatif
Pada masa pemerintahan Abu Bakar, khalifah dan pejabat administratif memiliki rangkap jabatan sebagai hakim juga. Namun, seiring perkembangan kekuasan kaum muslimin, Umar berpikir bahwa kaum muslimin membutuhkan mekanisme administratif yang lebih mendukung sistem pemerintahan yang baik.
Karena itulah Umar memutuskan untuk memisahkan antara eksekutif dan yudikatif. Bersama dengan hal tersebut, Umar melakukan pengangkatan gubernur, ahlul halli wal aqdi, pendirian pengadilan, dan juga mengangkat hakim.
6. Ahlul halli wal aqdi
Ahlul halli wal aqdi merupakan lembaga yang dibuat untuk menetapkan penyelesaian dan kesepakatan atas suatu hal. Anggota lembaga ini berasal dari para ulama dan cendekiawan. Ada dua kriteria penting untuk anggota lembaga ini. Yaitu telah mengabdi di dunia politik, militer, dan misi Islam setidaknya selama 8 – 10 tahun, dan juga memiliki pengetahuan Islam dan Al-Qur’an yang memadai.
7. Kebijakan permusyawaratan terbuka
Di masa kepemimpinannya, Umar juga memulai kebijakan permusyawaratan terbuka. Musyawarah ini dilakukan di masjid ibu kota dan dihadiri oleh anggota majelis atau oleh Umar sendiri. Dalam musyawarah ini, setiap masyarakat boleh menyampaikan keluhan dan menyelesaikan masalah bersama.
Termasuk juga oranng yang kontra dengan pemerintahan, wanita, anak-anak, orang tua, dan non muslim. Seluruh lapisan masyarakat memiliki hak penuh dan pendapatnya akan dicatat dan disampaikan dengan baik.
8. Kebijakan pembangunan pusat perbendaharaan negara
Atas usul Walid bin Hisyam, Umar pun membangun Pusat Perbendaharaan Negara atau baitul maal di Madinah dan kota – kota lainnya. Harta yang tersimpan di baitul maal kemudian digunakan untuk kepentingan umat. Untuk mengelola perputaran uang di baitul maal, Umar pun membuat sistem tadwinud diwan atas usulan salah seorang warga.
9. Kebijakan pembangunan infrastruktur
Pada masa pemerintahannya, Umar juga membangun berbagai infrastruktur. Mulai dari pembangunan kota, saluran air, dan bangunan penunjang pemerintahan seperti bangunan keagamaan, bangunan militer, dan bangunan sipil. Bersama dengan pembangunan tersebut, dibangun juga fasilitas penunjang seperti jalan dan jembatan.
Kota Madinah pun tidak luput dari pembangunan. Pada 17 H, Umar memerintahkan perbaikan jalan di Madinah, pembangunan tempat berteduh antara Makkah dan Madinah, pembersihan dan juga penggalian sumur baru. Dengan begitu, jamaah haji yang datang bisa menjalankan ibadah haji dengan baik.
Adapun kebijakan-kebijakan islam kepemimpinan Umar bin Khattab yang bermanfaat hingga kini, diantara lain:
1. Libur pada Hari Jumat
Pada masa Umar bin Khattab, hari Jumat ditetapkan sebagai hari libur nasional dengan pertimbangan sebagai waktu menyiapkan diri mengikuti Sholat Jumat. Usulan ini kemudian menjadi sistem yang terus diikuti hingga saat ini, khususnya bagi lembaga pendidikan Islam di tingkat pesantren.
2. Kalender Islam
Mulai dikembangkannya penanggalan hijriyah. Dalam bidang astronomi, umat Islam mulai mengembangkan ilmu falak atau ilmu astronomi Islam serta penanggalan hijriyah. Hal ini memiliki peran besar terhadap pelaksanan kegiatan ibadah umat islam, yaitu dalam hal penetapan tahun Hijriyah. Penetapan tanggal hijriyah berdasarkan tradisi Islam dilaksanakan dengan mengikuti kalender peredaran bulan.
Selanjutnya ada pula kebijakan-kebijakan lain, yaitu sebagai berikut:
3. Sholat Tarawih Berjamaah
Semenjak meninggalnya Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, para sahabat terus menjalankan shalat tarawih dengan berpencar-pencar atau bermakmum kepada imam yang berbeda-beda. Akhirnya Umar bin Al-Khattab menyatukan mereka untuk bermakmum kepada satu imam. Abdurrahman bin Abdul Qariy berkata:
Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat menjalankan sholat tarawih dengan terpencar atau dengan imam yang berbeda-beda. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab menyatukan mereka untuk bermakmum pada satu imam.Abdurrahman bin Abdul Qariy berkata: “Suatu malam di bulan Ramadhan, aku keluar bersama Umar bin Khattab menuju masjid. Ternyata kami dapati manusia berpencar-pencar di sana sini. Ada yang shalat sendirian, ada juga yang shalat mengimami beberapa gelintir orang. Beliau berkomentar: “(Demi Allah), seandainya aku kumpulkan orang-orang itu untuk sholat bermakmum kepada satu imam, tentu lebih baik lagi”. Kemudian beliau melaksanakan tekadnya, beliau mengumpulkan mereka untuk shalat bermakmum kepada Ubay bin Ka’ab Radhiyallahu’anhu. Abdurrahman melanjutkan: “Pada malam yang lain, aku kembali keluar bersama beliau, ternyata orang-orang sudah sedang shalat bermakmum kepada salah seorang qari mereka”. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Uwattha (I:136-137), demikian juga Al-Bukhari (IV:203), Al-Firyabu (II:73, 74:1-2), Dan juga Ibnu Abi Syaibah (II:91:1).
4. Pendidikan dan Lembaga Kajian Al Quran
Khalifah Umar bin Khattab menaruh kepedulian yang besar terhadap bidang pendidikan. Oleh karena itu pada masa kepemimpinannya pendidikan pun berkembang. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Khalifah Umar bin Khattab meresmikan Madinah sebagai kota negara Islam dan sebagai pusat pembentuk hukum-hukum Islam. Pada masa kepemimpinannya sebagai khalifah, salah satu agenda Umar bin Khattab adalah menjadikan Madinah sebagai pusat kajian Al-Quran dan fikih.
5. Menerangi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dengan Lampu.
Umar bin Khattab merencanakan menerangi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, bahkan berlanjut hingga setelahnya. Ali bin Abi Thalib berkata, “Semoga Allah menerangi Umar di kuburnya, sebagaimana ia menerangi kita di masjid ini.”
Penulis: Raisya Audyra