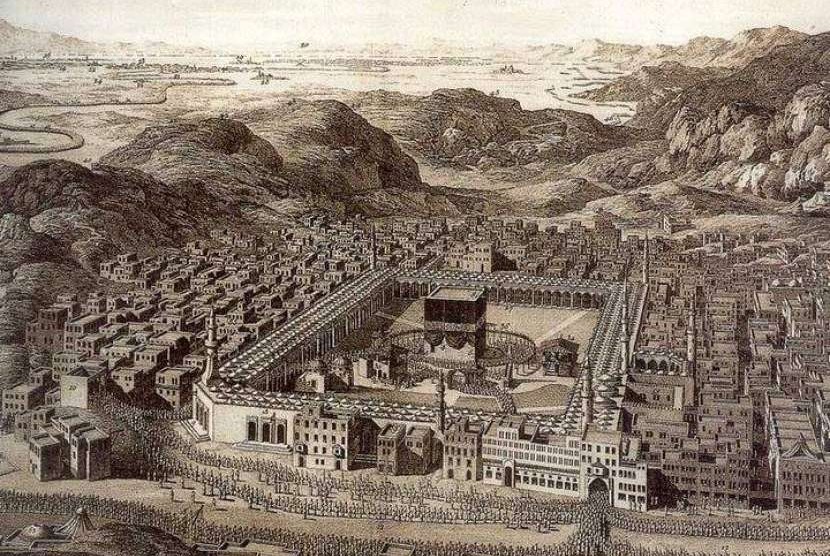Bolehkah sebagian daging hewan kurban kita makan ??
Bagaimana hukum berkurban? Bolehkah sebagian daging hewan kurban kita makan, dan kepalanya kita berikan kepada tukang potong sebagai upah, serta kulitnya kita jadikan sebagai rebana?
Berkurban atau mendekatkan diri kepada Allah dengan menyambelih hewan tertentu pada Hari Raya Idu Adha dan dua atau tiga sesudahnya adalah salah satu ajaran agama yang ditegaskan dalam al-Qur’an (QS. Al-Kautsar [108]: 2 dan QS. al-Hajj [22]: 36). Imam Abu Hanifah menilainya wajib bagi setiap orang yang mampu, berdasaarkan sabda Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah: “Barang siapa memiliki kemampuan dan tidak mau berkurban, maka hendaknya dia tidak mendekati tempat shalat kami.”
Menurut penganut paham Abu Hanifah, ancaman ini menunjukkan wajibnya berkurban, sementara madzhab lain menilainya sebagai anjuran yanga amat ditekankan (sunnah mu’akkadah) berdasarkan sekian banyak hadist. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, “Aku diperintahkan berkurban, sedang itu sunnah untuk kalian.”
Ibnu Abbas berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda, “Tiga hal menjadi kewajiban atas diriku, dan ketiganya merupakan anjuran bagi kalian, yakni (shalat) witir, menyembelih kurban, dan shalat dhuha.”
Menurut madzhab Syafi’i, anjuran ini cukup dilaksanakan sekali seumur hidup. Di sisi lain, dianjurkan pula agar setiap kepala keluarga atau salah seorang keluarga hendaknya berkurban untuk dirinya (kalau belum) atau atas nama salah seorang keluarganya. Para ulama juga sepakat bahwa hewan yang boleh dikurbankan haruslah unta atau sapi atau kerbau (maksimal seekor untuk seorang) yang sehat dan sempurna, baik jantan maupun betina.
Ihwal memakan daging kurban yang di sembelih,mayoritas ulama membolehkannya. Jika kurban itu dilakukan untuk memenui nazar,maka Abu Hanifah dan Syafi’i melarang orang bersangkutan dan keluarganya memakan dagingnya. Dalam madzhab Maliki, Hanafi, dan Hanbali, disunnahkan bagi orang yang berkurban untuk menggabungkan antara membagikan dan memakannya. Bahkan, seandainya dia memakan semuanya atau menyimpannya selama tiga hari kemudian, maka yang demikian itu diperbolehkan menurut madzhab Hanafi dan Maliki, walaupun hukumnya tidak dianjurkan (makruh).
Dalam madzhab Hanafi dan Hanbali, dianjurkan untuk membagikan daging kurban sepertiga untuk dirinya dan keluarganya, sepertiga untuk teman-teman, meskipun kaya, dan sepertiga lainnya untuk fakir miskin. Menurut mereka, hal ini berdasarkan firman Allah: … Kemudian jika (hewan yang dikurbankan itu) telah roboh (mati), maka makanlah sebagian darinya, dan berilah makan orang yang rela dengan apa yang ada padanya(yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta, … (QS. al-Hajj [22]: 36).
Imam Malik tidak menetapkan kadar tertentu. Penganut madzhab ini berpegang pada sekian banyak hadist yang menganjurkan agar memakan, memberi makan, dan menyisihkannya untuk disimpan. Hadist-hadist itu dapat dilihat, antara lain, dalam kitab Nayl al-Awthar, jilid kelima. Alasan lain tentang kebolehan menyisihkan adalah hadistyang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi SAW. bersabda, “Aku tadinya melarang kalian menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari karena adanya ‘Addafat’ (orang-orang yang datang dari pegunungan mengharapkan bekal akibat paceklik). Kini, telah datang kelapang dari Allah. Maka, simpanlah sekehendak kalian.” (HR. Muslim).
Menjual sesuatu yang berkaitan dengan hewan kurban tidak dibenarkan, baik kepala, daging, kulit, atau bulunya. “Barang siapa menjual daging hewan kurbannya, maka tidak ada (sah) kurbannya,” begitu sabda Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh al-Hakim dan al-Baihaqi. Tidak juga dibenarkan memberikannya sebagia upah kepada penyembeli. Tetapi memberikannya sebagai hadiah kepadanya atau orang yang wajar menerimanya, maka hal itu dibenarkan.
Di sisi lain, yang berkurban atau yang lainnya dapat memanfaatkan kulit hewan kurbannya untuk rebana atau apa saja. Wallahualam Bisshawab