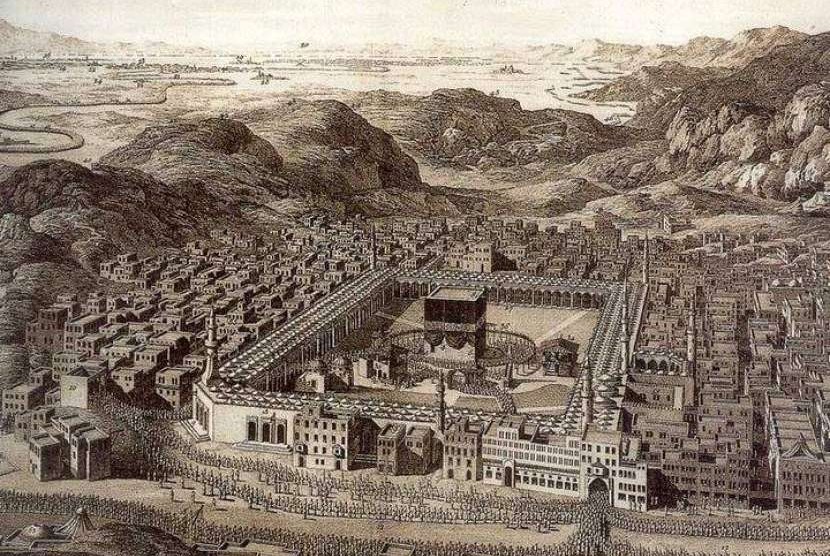Dahulukan Makan atau Shalat ??
Ada hadist yang menyatakan bahwa menahan buang air kecil dan buang angin tidak ada shalat bila makanan telah siap sedia ( jadi harus makan dulu baru shalat ). Bagaimana maksudnya?
Imam Muslim meriwayatkan dalam Shahih-nya melalui istri Nabi, ‘Aisyah RA., bahwa dia mendengar Nabi SAW. Bersabda, “Tidak ada shalat dengan hadirnya makanan, dan tidak ada shalat pula bagi orang yang didorong oleh kedua yang buruk ( air kecil dan air besar ).”
Para ulama memasukkan “buang angin” atau kentut di dalam larangan ini. Pengarang kitab Subul as-Salam menyatakan bahwa kalau yang bersangkutan tidak didorong oleh hal-hal itu, dan hanya sekedar merasakan adanya “panggilan” untuk membuangnya, maka ini tidak termasuk dalam larangan diatas. Bahkan, seandainya dorongan itu ada, maka ini hanya dipahami sebagai larangan makruh, bukannya membatalkan shalat.
Akan halnya menyangkut sholat dan tersedianya makanan, hadist yang diriwayatkan Imam Muslim diatas dipahami dalam arti larangan iqamah (mengajak untuk segera melaksanakan shalat ) ketika makanan sudah dihidangkan. Ada sekian banyak hadist serupa. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW. bersabda, “Jika makan malam telah dihidangkan, maka dahulukanlah bersantap malam, sebelum shalat maghrib.”
Ada juga riwayat yang menyebutkan shalat secara mutlak. Ibnu Hazm berpendapat bahwa semua shalat harus ditunda bila makanan telah tersedia, dan tidak sah mengerjakan shalat dalam situasi demikian. Ada juga yang membatasi shalat dalam hal ini sebagai shalat maghrib saja atau ketika sedang berpuasa. Imam Syafi’i memahami larangan ini hanya bagi orang yang sedang lapar saat itu. Sementara itu, Imam al-Ghazali memahaminya dalam konteks kekhawatiran rusaknya makanan yang tersedia itu.
Syarat tambahan lainnya adalah ‘tersedianya waktu yang tersisa sesudah makan untuk melaksanakan shalat diwaktu shalat yang telah ditetapkan oleh agama.” Bagaimanapun juga, mayoritas ulama berpendapat bahwa laranga diatas hanya mengandung arti makruhnyashalat, bukan tidak sahnya shalat. Kemakruhan ini berkaitan dengan terganggunya konsentrasi yang mengakibatkan berkurangnya kekhusyukan. Wallahualam Bisshawab