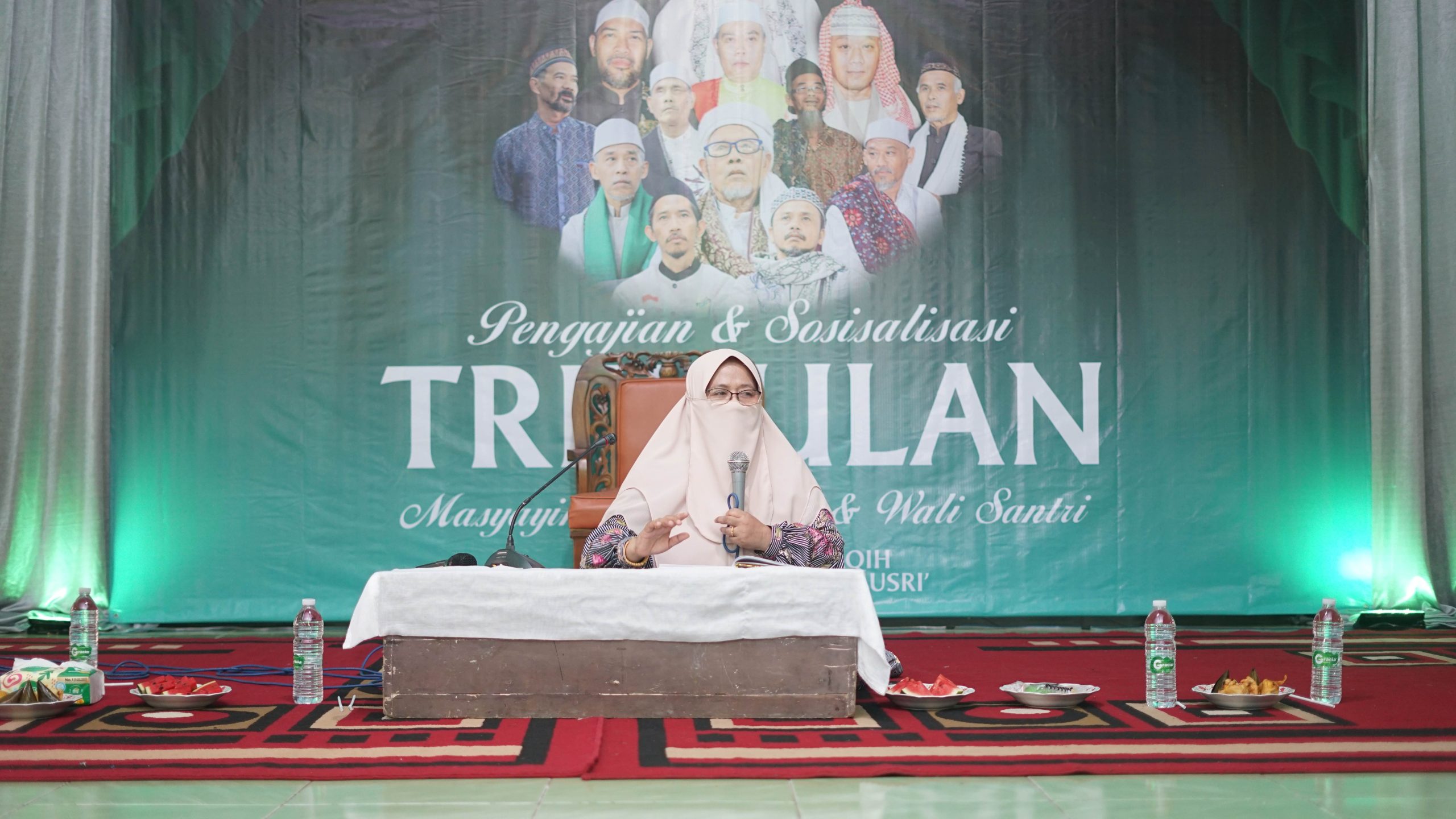Di Balik Tuduhan Feodalisme dalam Tubuh Pesantren
Pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisonalis dengan sederet prestasinya telah berperan dalam harmoni kehidupan umat, pesantren dengan jebolannya telah banyak meraih prestasi dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan juga politik. Sebut saja presiden keempat Republik Indonesia, yakni KH Abdurrahman Wahid adalah sosok jebolan pesantren yang meraih ketiga prestasi di atas sekaligus.
Namun akhir-akhir ini pesantren mendapatkan klaim yang dapat menyinggung sekelompok kaum sarungan, lontaran kata ‘feodalisme’ dari beberapa pihak yang disandarkan terhadap kehidupan pesantren nampaknya telah memberikan konotasi buruk kepada figur pesantren yang meliputi kiai dan santri. Klaim demikian sangatlah memberikan kesan terhadap khalayak banyak, bahwa sistem pesantren sama halnya dengan sistem sosial yang mengagung-agungkan jabatan atau pangkat dan bukan mengagung-agungkan atas prestasi kerja.
Seklumit Tentang Feodalisme
Terminologi feodalisme berasal dari era Romawi. Yang Menurut Dictionary, istilah feodalisme menyebar di Eropa pada abad ke delapan, yang mana bawahan dilindungi oleh para tuan yang harus mereka layani dalam perang (Alexanderandi, dan Alifian, 2024).
Pada hari ini feodalisme dihubungkan dengan maknanya yang berkaitan dengan apa pun yang memiliki hubungan vertikal, yang mana bawahan diharamkan diberikan hak memimpin bukan berdasarkan kelemahan prestasi atau etos kerja yang ia miliki, akan tetapi hak kepemimpinan hanya diberikan kepada seseorang atas dasar kekayaan, senioritas dan sebagainya (baca: meritrokasi).
Mirisnya, pesantren menjadi objek istilah ‘feodalisme’ oleh mereka, entah dengan tujuan apa yang diinginkannya. Dengan sosok kiai sebagai pimpinan mutlak pesasntren, mereka dengan entengnya menyematkan istilah feodalisme di dalam tubuh pesantren.
Tradisi Pesantren
Kiai dengan otoritas keagamaannya memiliki kedudukan besar yang telah melahirkan hierarki kekuasaan yang secara eksplisit diamini di dalam lingkungan pesantren. Tetapi, kekuasaan kiai berdiri di atas moralitas dan keunggulan pengetahuan ketuhanan (agama) serta kepribadiannya yang bersahaja dan terbuka. Karena umumnya praktik kehidupan kiai sangatlah sederhana, egaliter, dan mandiri (Muhammad, 2020).
Cita-cita pendidikan pesantren, umumnya adalah dapat berdiri sendiri dan tidak menggantungkan dirinya terhadap pihak lain kecuali kepada Allah. Para kyai selalu memberikan perhatian dan mengembangkan watak pendidikan individual kepada para santrinya, para santri diperhatikan tingkah laku moralnya secara teliti. Mereka diperlakukan secara hormat layaknya titipan Tuhan yang harus disanjung (Dhofier, 2011).
Pengagungan dan penghormatan terhadap kiai bukanlah hal yang tidak berdasar, melainkan dengan kharisma paripurna yang dimiliki kiai, sebagi figur pemimpin di pesantren dengan segala keilmuannya lah yang menjadi alasan dasar penghormatan tersebut. Santri melihat kiai sebagai sosok yang memahami kehendak Tuhan dengan pemahamannya yang luas atas teks-teks keagamaan, di sisi lain kiai memiliki hubungan dekat dengan Tuhan.
Dengan begitu, kepatuhan mutlak santri kepada kiai bukanlah sebagai manifestasi dari penyerahan total kepada kiai yang memiliki otoritas, tetapi karena keyakinan santri terhadap kiai sebagai penyalur kemurahan Tuhan kepada murid-muridnya. Oleh sebab itu peranan kiai sangatlah penting bagi kehidupan santri meliputi banyak aspek.
Zamakhsyari Dhofier dalam Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia (2011), menyampaikan bahwa “kedudukan guru sangatlah penting dalam kehidupan muridnya, sehingga perlu adanya pertimbangan dalam memilih guru. Dalam Ta’lim Al-Muta’allim dijelaskan agar menimbang-nimbang guru yang akan dipilihnya, paling tidak dua bulan sehingga ia yakin bahwa gurunya adalah benar-benar orang yang ‘alim, arif, dan selalu menahan diri dari perbuatan yang dilarang, dimakruhkan, atau yang belum memiliki ketentuan dalam Agama (wira’i).”
Oleh karenanya, tidak semua perintah dan kata-katanya harus diindahkan tanpa adanya pertimbangan syar’i dan rasio. Sebagai contoh, Gus Baha’ (KH. Baha’uddin Nursalim) pernah menjelaskan bahwa “pertanyaan Nabi Musa terhadap gurunya, Nabiyullah Khidir ketika membunuh anak kecil yang tak berdosa, adalah sebagai peneguhan Nabi Musa terhadap syari’atnya”.
Di samping itu, perlunya menimbang guru yang hendak dipilih mengartikan tujuan kepatuhan murid terhadap gurunya agar tidak terjebak dalam lubang kesesatan dan kemaksiatan. Tentu saja dalam kemaksiatan atau dalam tingkah laku yang tidak selaras dengan ajaran Islam kepatuhan haruslah ditidak hadirkan.
Kiranya dapat dipahami bahwa, sistem hierarki di pesantren bukan semata-mata pengkultusan figur secara buta, melainkan menimbang dari etos kerja dan intelektualitas para kiai. Lebih lanjut Dhofier (2011) membeberkan sistem kompleks yang tercipta dalam lingkungan pesantren, dari kiai sebagai pemimpin pesantren, kiai muda, asatid, santri senior, dan santri junior, itu semua atas dasar kematangan pengetahuan dalam bidang Agama Islam.
Pesantren Menghalalkan Meritrokasi
Fakta lain bisa disaksikan dengan tradisi adu argumen dalam Bahstu Al-Masa’il di beberapa banyak pesantren, tidak sedikit santri yang membantah argumen kiai atau seniornya. Pasalnya santri tidak sepenuhnya menerima apa yang dikatakan kiai atau seniornya dengan kaku yang dapat menghambat kebebasan berpendapat dan inovasi. Karena ini adalah tradisi kritis keilmuan yang mesti dilestarikan untuk melatih berfikir kritis dalam memahami cita-cita teks keagamaan, sekaligus bukti bahwa tradisi intelektual pesantren tidak dimonopoli oleh para atasannya.
Tak hanya itu, tidak sedikit dari pesantren yang mengangkat santrinya untuk meneruskan hak kepemimpinannya. Biasanya santri yang berintelektual tinggi akan dijadikan menantu dari sang kiainya, ini menandakan bahwa sistem pesantren tidak mengharamkan meritrokasi yang dapat memberikan hak memimpin dengan alasan prestasi yang baik dan etos kerja yang mutu, yang bukan berdasar pada kekayaan, senioritas, atau warisan belaka.
Sebagai contoh adalah pondok pesantren Lirboyo yang terkenal dengan sosok tiga tokoh besarnya, yakni KH Abdul Karim sebagai pendirinya, KH Marzuqi Dahlan sebagai menantunya, dan KH Mahrus Ali juga sebagai menantunya.
Penutup
Istilah Feodalisme yang memiliki konotasinya yang relatif buruk, adalah problematika dalam hubungan vertikal semua manusia, seperti tuan dan buruh, bos dan koleganya, bahkan guru dengan muridnya. Oleh karenanya, ia menjadi problematika yang relatif sesuai dengan siapa yang melakukannya.
Sementara, problematika yang sangat fundamental dalam istilah feodalisme adalah kebebasanya dalam berfikir. Seperti yang dikatakan Rocky Gerung sang pengamat politik ternama di Indonesia, Rocky mengatakan “dalam sejarahnya bahwa para father founding Indonesia dahulu sangat mengagumkan pemikiran dan kebebasan berpendapat. Namun kenapa semua itu saat ini terkesan hilang?” (Alexanderandi, dan Alifian, 2024).
Sedangkan dalam tradisi intelektual pesantren masih mengagunmkan pemikiran dan kebebasan berpendapat yang dibuktikan dalam forum diskusinya, yaitu Bahastul Masa’il.
Pada akhirnya, tuduhan feodalisme terhadap pesantren sering kali tidak memahami konteks dan nilai-nilai yang mendasari hierarki dan tradisi pesantren. Hierarki dalam pesantren lebih bersifat fungsional dan didasarkan pada keilmuan dan moralitas, bukan pada kekuasaan yang sewenang-wenang.
Baca juga : Sikap Tawadhu’ Dan Bantahan Tuduhan Feodalisme Di Pesantren

Pewarta : M Wildan Musyaffa